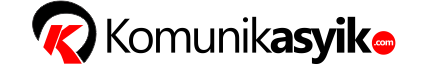Regulasi Media Baru Atas Tayangan Pornografi
Oleh: Yons Achmad
(Ketua Gerakan Penyiaran Ramah Anak/GEPRA. Pendiri Komunikasyik.com)
Ada fakta memprihatinkan. Angka permintaan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri Jawa Timur mencapai 569 pasangan. Dispensasi dilakukan untuk dapat menikah di bawah usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Para pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Kediri berusia antara 15-17 tahun. Sebagian besar dari mereka telah hamil di luar nikah. Dalam catatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, tingginya anak hamil di luar nikah disebabkan oleh empat faktor yaitu ekonomi, hukum adat, pendidikan dan teknologi yakni tontonan pornografi menjadi pemicu utama.
Di sini, tanpa mengabaikan faktor lainnya, secara khusus saya akan menyoroti perihal pornografi. Di mana, yang dimaksud tayangan pornografi dalam ketentuan yang diberlakukan, merupakan suatu tayangan melalui bentuk media komunikasi yang menampilkan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) baik dalam bentuk gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain yang bertujuan untuk membangkitkan birahi (gairah seksual) atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No 03 tahun 2007 tentang standar program siaran, pelanggaran dan pembatasan program siaran seks, jika hal ini masih berlaku, memuat aturan tegas tentang hal itu. Semisal lembaga penyiaran televisi dilarang menampilkan adegan yang secara jelas didasarkan atas hasrat seksual. Dibatasi menyajikan adegan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, dan sungkem. Dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatanhubungan seks, secara eksplisit dan vulgar.
Selanjutnya, dilarang menyiarkan suara suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks. Dilarang menyajikan percakapan, adegan, atau animasi yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks. Dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan. dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah
Sementara, Data KPAI menyebutkan selama 2022 terdapat 87 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan cyber crime. Fakta demikian tentu tak cukup disikapi dengan prihatin semata. Menjadi perlu sebuah gerakan sistematis agar dikemudian hari fakta demikian bisa tertangani dengan baik. Sebuah gerakan yang melibatkan kolaborasi dan sinergi berbaagai pihak untuk hadirnya sebuah tayangan yang ramah bagi anak.
Menyoal tayangan pornografi, terutama di televisi dan radio, tentu hal ini menjadi ranah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Beragam tayangan berbau pornografi di media elektronik itu sudah terpatau melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan KPI. Berbagai teguran dan sanksi sudah diberlakukan bagi stasiun yang melanggar. Pertanyaannya, bagaimana dengan media baru (media sosial)? Siapa yang berwenang dalam memantau dan mengawasi? Tidak ada. Kecuali kalau partisipasi publik kuat. Misalnya penolakan kasus tertentu seputar tayangan berbau pornografi muncul. Lantas menjadi viral, kemudian advokasi dan penolakan kuat, biasanya Kominfo baru bertindak. Selebihnya, sering luput dalam pantauan.
Sejauh ini, pengawasan yang menjadi kewenangan KPI sendiri (berdasarkan UU Penyiaran No.32 tahun 2002) hanya meliputi media penyiaran, tidak dapat menjangkau media di luar itu seperti media sosial atau streaming. Padahal banyak masyarakat yang mengeluh dan melaporkan persoalan media baru ke KPI. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran warganet (netizen). Alih-alih memberikan apresiasi kepada KPI atas performa pengawasan, justru banyak juga yang menolak kewenangan pengawasan media baru oleh KPI karena dinilai bakal memunculkan problem baru, salah satunya berupa pengekangan kebebasan berekspresi. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPI misalnya memberikan jaminan bahwa bukan pengguna (user) nya yang bakal diatur, akan tetapi platform medianya. Kini, ruang mendioalogkan persoalan ini masih terbuka lebar.
Bercermin dari negara lain. Misalnya, seperti pernah dipaparkan olehWendratama dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) (2022) dalam diskusi bertajuk “Revisi UU Penyiaran: Urgensi Regulasi Konten Streaming OTT” yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, (26/7). Regulasi telah dibuat Uni Eropa, yang mengatur siaran televisi tradisional yang tayang melalui free to air, layanan video on demand seperti Disney Hotstar, Netflix dan Amazone Prime dan juga video sharing seperti Youtube. Pada prinsipnya aturan ini bertujuan menciptakan arena bermain yang setara bagi media audiovisual baru dan melindungi khalayak dari konten berbahaya dan hasutan untuk melakukan tindak kekerasan dan kebencian. Selain itu, untuk melestarikan keberagaman budaya yang diimplementasikan dengan aturan 30% film Eropa harus muncul dalam katalog video on demand seperti Netflix. Tujuan lainnya adalah serta menjaga pluralisme media, sehingga jangan sampai ada giant tech yang mendominiasi audien.
Selanjutnya, masing-masing anggota Uni Eropa, berkewajiban membuat aturan turunan secara nasional yang selaras dengan kepentingan setiap negara. Setidaknya ada tiga platform yang memiliki audiens paling besar dan mampu memberi pengaruh terhadap persepsi publik atas realitas. Prancis mewajibkan tiga platform besar seperti Netflix, Amazone Prime dan Apple TV, untuk mengalokasikan 26% pendapatannya di negara itu untuk produksi konten nasional. Kebijakan serupa juga diambil Italia, dengan aturan alokasi 20% , sedangkan Spanyol mengatur sebesar 3,5 %. Pertanyaannya, apakah regulasi demikian juga berlaku di Indonesia. Saya kira, di Indonesia regulasi dan kontrol demikian masih belum diatur secara detail. Hasilnya, kita bisa lihat seperti sekarang. Tayangan-tayangan apapun bebas memapar pemirsa tanah air, termasuk anak-anak.
Satu-satunya kekuatan yang tersisa kini hanya partisipasi pubik. Sejauh mana publik peduli atas penyiaran yang ramah anak, penyiaran yang lebih beradab, sejauh itulah masyarakat bisa ikut berkontribusi terhadap hadirnya tayangan-tayangan yang bermutu dan bagus bagi tumbuh kembang anak. Di sini, tingkat literasi media, dalam arti tingkat keberdayaan masyarakat untuk mampu memilah, menyaring dan menolak tayangan-tayangan yang dinilai merusak masa depan anak-anak sangat menentukan. Kita tentu berharap, partisipasi publik terhadap tayangan ramah anak semakin besar dari waktu ke waktu. Sementara, institusi yang bersinggungan dalam problematika ini seperti Kementerian Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPA), KPAI dan KPI, terus bersinergi mewujudkan tayangan yang ramah anak dengan beragam program pemberdayaan dan pencerdasan publik serta kajian yang relevan. []