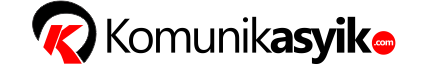Sebuah kampus Ilmu Komunikasi di Jawa Tengah, merayakan hari jadinya dengan mengangkat sebuah tema “Komunikasi untuk Resiliensi.” Saya kira, tema demikian sangat relevan dengan era pandemi yang masih kita hadapi sekarang ini. Kenapa? Ketika banyak orang secara tiba-tiba menghadapi beragam masalah dan kesulitan. Di saat itulah, bagaimana seseorang mengambil sikap sangat menentukan apakah kemudian bisa bertahan, bangkit dan melalui masa-masa sulitnya. Atau malah menjadi tumbang dan hancur lebur.
Resiliensi sendiri adalah istilah populer dalam dunia psikologi. Sebuah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam kondisi sulit. Banyak hal yang disarankan untuk bisa memiliki kemampuan semacam itu.
Para ahli psikologi bersepakat setidaknya ada 7 cara agar bisa melakukannya. Diantaranya, regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif. Mereka juga sepertinya bersepakat bahwa setiap individu mustahil memiliki keseluruhan kemampuan tersebut dengan baik.
Tapi, setidaknya beberapa diantaranya bisa diterapkan untuk membantu resiliasi diri. Untuk bisa bangkit dari keadaan, melihat beberapa aspek di atas, saya tertarik dalam soal regulasi emosi. Ya, kondisi emosi yang dikendalikan dengan baik, bakal membantu seseorang ke luar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Tentu dengan sebuah solusi yang baik, bukan sebaliknya.
Dalam pengelolaan emosi ini, konon ada dua hal penting yang mesti diperhatikan, yaitu ketenangan (calming) dan fokus (focusing). Ketenangan dalam menghadapi masalah dan fokus kepada solusi, bukan pada masalah itu sendiri. Selanjutnya apa? Saya kira semua itu perlu dikomunikasikan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.
Intan Savitri, Doktor psikologi Universitas Indonesia pernah mengembangkan apa yang disebut dengan “Narrative Writing Therapy”. Dalam pandangannya, memaknai hidup dengan menuliskannya bisa menjadi salah satu solusi dalam meringankan beban berat yang kita hadapi. Di sini, kita belajar menceritakan apa yang kita alami, merasakan peristiwa yang kita alami, belajar memaknai dan kemudian menemukan jalan untuk melewati semuanya.
Itu jalan komunikasi diri yang bisa kita tempuh. Ketika kita sudah selesai dengan diri sendiri, maka saatnya berkomunikasi dengan orang lain diperlukan. Sebab, seberapa besar masalah yang kita hadapi. Seberapa berat beban masalah yang kita pikul, bakal terselesaikan jika dikomunikasikan. Kepada orang yang tepat, kepada lembaga yang tepat. Ke semuanya itu barangkali sebuah metode ilmu pengetahuan “Barat” yang dikembangkan untuk ikut berkontribusi sebagai basis teori maupun panduan dalam meyelesaikan problem psikologi manusia.
Tapi, apa yang kurang dari semua itu? Jelas. Sentuhan aspek religi. Bagi seorang muslim, sebuah ketenangan bisa didapatkan ketika dia mau kembali berkomunikasi dengan Tuhannya (Allah). Kalau banyak orang melakukan meditasi, seorang muslim bisa menempuh jalan keheningan agar bisa melongok ke dalam diri. Salah satunya adalah shalat tahajud di keheningan malam.
Di situlah ketenangan didapatkan dan jawaban ke luar dari beragam permasalahan bisa kita temukan. Itulah salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk melalui semua itu. Terakhir, baru kita percayai apa yang orang sering sebut sebagai optimisme. Ya, itulah jalan membangkitkan harapan. Kenapa harus optimistis? Jelas, karena pesimisme tidak akan pernah menghasilkan apa-apa.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. CEO Komunikasyik.com)